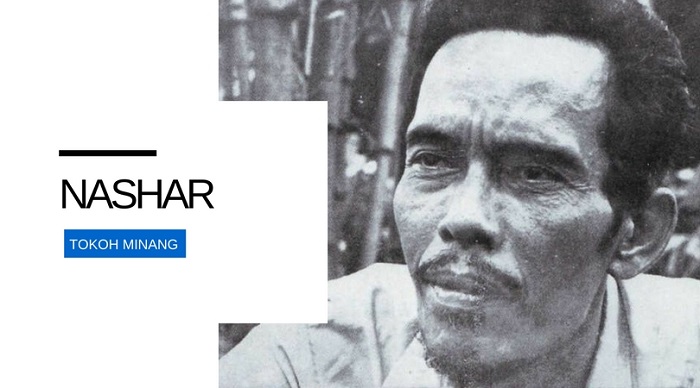Kehidupan pelukis Nashar tercermin dari goresan kuasnya diatas kanvas yang penuh teka-teki, sulit dimengerti. Dalam berkarya, ia memilih jalan sunyi, marginal dari pasar.
Padahal, Nashar begitu produktif melukis. Ratusan lukisannya tersebar di beberapa kolektor dan galeri. Lukisannya pun bisa dikatakan bernilai tinggi, dan sebetulnya bisa menjadikan ia kaya. Tapi nasib berkata, hingga akhir hayat, lelaki asal Pariaman ini tidak punya sepetak rumah pun.
Ia selalu membawa sketsa, ditulis lalu dituangkan di atas kanvas. Lukisan dia bukan tak dilirik pasar, justru ia memilih untuk tidak dalam dekapan pasar atau melukis untuk pasar.
Mendiang Jeffrey Hadler (sejarawan dari University of California, Barkeley), beberapa tahun lalu, datang ke Universitas Andalas, Padang, dalam rangka meriset Nashar.
Dalam kesempatan tersebut, Jeffrey Hadler mengatakan Nashar adalah pelukis Indonesia yang sangat idealis, memilih marginal dari pasar. Ia melawan arus komersialisasi dari seorang pelukis.
Nashar lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 3 Oktober 1928. Sedari kecil sudah hidup dalam gelimang kemiskinan. Ketika zaman penjajahan Jepang, Nashar diboyong merantau ke Jakarta oleh keluarganya.
Nashar lebih menjadi liar ketika ayahnya menikah lagi. Ia memilih dunia seni lukis, ketimbang menjalankan keinginan ayahnya agar menjadi pedagang.
“Nashar , orang Pariaman yang besar di rantau. Ketika zaman revolusi, ia bergabung dengan Seniman Muda Indonesia (SMI), dan mengikuti lembaga itu pindah ke Madiun dan Solo. Nashar juga pernah tinggal di Yogyakarta di sanggar Affandi,” jelas Jeff, panggilan Jeffrey Hadler.
Titik penting Nashar dalam dunia lukis adalah ketika dibaptis ‘tak berbakat’ oleh Bapak Seni Rupa modern Indonesia Selo Sudjojono.
Ajip Rosidi dalam buku Mengenang Orang Lain: Sejumlah Otobiografi, menuliskan, Pertemuan Nashar dengan Sedjojono bermula ketika Nashar mendaftar belajar melukis yang diselenggarakan Keimin Bungka Sidhoso -Pusat Kebudayaan Jepang-, yang dipimpin Sudjojono.
Mungkin saja maksud Sudjojono baik, supaya Nashar terus belajar tiada akhir. Dan kata-kata Sudjojono pula kemudian menjadi cemeti bagi Nashar untuk membuktikan bahwa dia berbakat.
Dimata Ajip, Nashar orangnya begitu keras kepala. Ia pantang menyerah untuk terus bisa membuktikan bisa melukis, terutama kepada Sudjojono yang menyepelekannya.
Kepada kawan-kawannya sesama pelukis dan juga mahasiswanya kelak, Nashar sering melafalkan kalimat seperti ini, “Bila kau tak memiliki bakat, kau harus menerobos tembok yang memisahkan tidak berbakat dan berbakat itu. Dengan begitu kau tahu, apakah kau memang tidak berbakat atau justru berbakat”.
Hari-hari Nashar sebetulnya adalah tahun 1960-an dan 1970-an. Periodik dimana dia begitu menanjak dalam berkarya, dan masa-masa kegetiran yang tertuang dalam Surat-Surat Malam yang ditulis tahun 1976.
Selepas dari Yogyakarta, Nashar hijrah ke Jakarta. Menurut Jeff, ia tinggal di rumah Lutan Madjid, tokoh dan sesepuh partai Murba. Sebelumnya, Tan Malaka pun pernah tinggal di sana.
Di rumah Lutan, Nashar bersentuhan dengan karya-karya Tan Malaka. Di Jakarta pun kemudian, Nashar melebur di Gabungan Pelukis Indonesia (GPI).
Kelak, melalui istri Lutan, Nashar mendapat jodohnya. Ia memperistri gadis Sunda. Buah percintaan mereka melahirkan 3 orang anak. Semuanya mengikuti jejaknya, jadi seniman terutama melukis.
Kesusahan hidup, menurut Jeff, tahun 1967, Nashar pernah diusir dari rumah kontrakan. Sejak itu, ia memilih nomaden.
Tinggal di Balai Budaya hingga sanggar lukis di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ), kelak berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta.
Di ruang-ruang demikian, ia menghabiskan malam dengan melukis, dan tidur atas tikar jika merasa sudah teramat mengantuk.
“Nashar dunia wisma. Tinggal di ruang-ruang budaya di Jakarta. Ada artikel yang menulis Nashar si pelukis miskin,” ujar Jeff dalam diskusi tentang Nashar di ruang pertemuan dekanat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Senin (22/7/2014).
Tahun 1963, Nashar ikut menandatangani Manifes Kebudayaan (Manikebu). Ia pun terlibat dalam pendirian LPKJ tahun 1976.
Nashar terkenal sebagai sosok yang idealis, konsisten menjaganya tanpa mau berkompromi terutama kemauan pasar.
“Ia tidak suka menjual lukisannya. Jika hanya butuh uang, ia lemparkan ke mahasiswa membeli lukisannya berapa pun duit adanya,” terang penulis buku Sengketa Tiada Putus yang meninggal dunia 11 Januari 2017 ini.
Nashar, dikatakan Jeff, memberi contoh melukis 100 persen murni melukis. “Nashar setia sekali dengan hati dan ide dia sendiri,” tukasnya.
Seperti juga hal yang ditulis Ajip, bagi Nashar, melukis adalah ekspresi diri, sehingga apa yang ia lukis merupakan pancaran dari dirinya. Melukis juga telah menjadi pacar sejati baginya hingga akhir hayat.
“Nashar adalah contoh monumental tentang dedikasi seniman terhadap keseniannya,” kata Ajip.
Dalam melukis, Nashar mengesampingkan teori. Ia mengembangkan kemungkinan-kemungkinan untuk menghasilkan karya yang imajinatif, dengan mendekonstruksi teori seni lukis.
Jeff sendiri berpendapat, Nashar beraliran sosio realis. Lukisannya absrak seperti pola hidupnya. Lukisan Nashar, kata Jeff, memiliki ciri khas seperti ada sesuatu organik, binatang, dan ada goresan terang.
Penyair Sumatera Barat Rusli Marzuki Saria menilai, Nashar sangat total dalam melukis. Ia menghayati bahwa orang Minang dalam membangun republik dalam kondisi kemelaratan.
Salah satu lukisan terkenal Nashar adalah Renungan Malam. Lukisan tahun 1978 ini, Nashar mengungkapkan bagaimana perasaannya pada bentuk-bentuk bebas dari representasi alam atau objek apa pun.
Dalam melukis atau pun diskusi dan menulis, Nashar selalu ditemani kretek dan juga bir.Budayawan Sumatera Barat Edi Utama yang mengenal dekat Nashar, mengatakan, diskusi sambil minum bir di Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah hobi Nashar.
“Ia seperti sufiistik. Ia tidak terlalu banyak memikirkan hidup,” ujar Bung Edi.
Menurutnya, Nashar hadir sebagai sebuah pribadi antara ada dan yang tiada.
Nashar meninggal di Jakarta, 13 April 1994, dalam usia 65 tahun. Ia meninggal dalam masa-masa sulit. Bahkan untuk biaya berobat, ia mencoba menjajakan lukisan melalui kawan-kawan. Namun itu tidak menolong.
Nashar memiliki tiga orang anak yakni Anwar Juliadi, Sugata Nashar, dan Buyung Sujali (Alm).
Sama seperti Nashar, anaknya juga menapaki dunia kepelukisan. Anwar begitu menghormati Nashar dan juga karyanya, kata Jeff, sementara Sugata melanjutkan estafet gaya hidup Nashar, dengan tetap tinggal di Balai Budaya Jakarta saat ini.